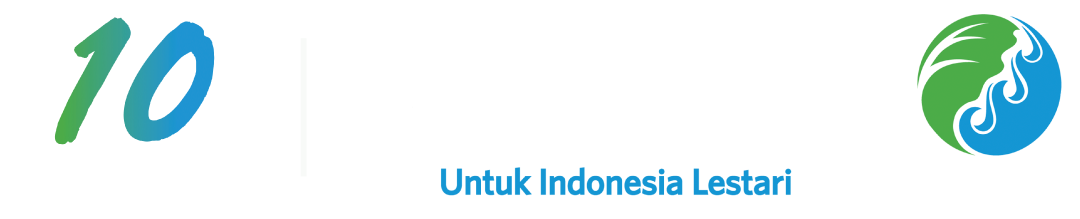Quote: Aji W Anggoro
Indonesia, dengan 3,44 juta hektar kawasan mangrove terbesar di dunia, perlu beralih dari konservasi berbasis komunitas ke konservasi yang dimiliki oleh komunitas. Pemberdayaan komunitas sangat penting untuk dampak jangka panjang, sebagaimana dibuktikan di Kabupaten Bengkalis.
Indonesia memegang tanggung jawab global dengan luas hutan mangrove yang mencapai 3,44 juta hektare. (Kemenhut – Peta Mangrove Nasional, 2024. Tak hanya menjadi negara dengan kawasan mangrove terbesar di dunia, Indonesia juga berada di garis terdepan upaya untuk menghadapi ketahanan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Baca juga: SIGAP Memberdayakan Desa-Desa Hutan
Ekosistem mangrove sendiri dikenal sebagai pelindung alami, menyerap energi gelombang, menyimpan karbon, dan menjadi tempat berkembang baik bagi ikan yang menjadi sumber pangan jutaan orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan konservasi berbasis komunitas semakin banyak diterapkan sebagai model praktis untuk melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan pesisir yang krusial ini, dan terbukti efektif.
Komunitas ataupun masyarakat lokal sering menjadi yang pertama menyadari perubahan lingkungan, merespons ancaman lokal, dan memiliki kepedulian paling besar terhadap masa depan ekosistem mereka. Namun, seiring meningkatnya skala dan kompleksitas upaya restorasi mangrove, semakin jelas bahwa keberlanjutan adalah kunci utama.
Untuk memastikan dampak jangka panjang, ketahanan komunitas, dan fungsi ekologis harus menjadi yang utama dibandingkan program-program jangka pendek yang sering kali berakhir setelah pendanaan selesai atau pihak eksternal mundur. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus beralih dari partisipasi berbasis komunitas ke konservasi yang dimiliki oleh komunitas. Bukan berarti mengabaikan pendekatan yang telah berhasil, melainkan memperkuat dan memperdalamnya. Konservasi berbasis komunitas adalah titik awal yang membuka pintu, membangun kepercayaan, dan menciptakan momentum. Namun dalam banyak kasus, program dirancang oleh pihak luar, diimplementasikan dengan dukungan lokal, lalu selesai tanpa sepenuhnya mewariskan visi jangka panjang.
Sebaliknya, konservasi yang dimili komunitas berarti masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi juga memimpin. Mereka merancang perencanaan, membuat keputusan penting, mengelola manfaat, dan membangun sistem tata kelola yang berakar pada pengetahuan lokal dan struktur sosial.


Perubahan ini bukan sekadar soal strategi, tapi soal cara pandang. Kepemilikan sejati membutuhkan waktu untuk dibangun dan tidak bisa buru-buru melalui lokakarya panjang dan rapat-rapat. Hal ini tergantung pada kemitraan jangka panjang, pengakuan hukum atas hak-hak, dan kemauan tulus dari pihak luar untuk berbagi kendali dan memberi ruang.
Pada saat yang sama, komunitas juga butuh waktu untuk membangun kapasitas dan kepercayaan diri untuk siap memimpin upaya konservasi sepenuhnya. Transisi dari “dimintai pendapat” menjadi “pengambil keputusan” adalah proses kompleks yang memerlukan waktu, namun sangat penting untuk hasil lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
Kami telah melihat bagaimana transisi ini terjadi di lapangan. Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bekerja sama dengan dua desa pesisir untuk memulihkan lebih dari 200 hektar ekosistem mangrove yang terdegradasi.
Awalnya, inisiatif ini mengikuti struktur umum: YKAN menyediakan keahlian teknis, desain program, dan strategi konservasi, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana lapangan. Namun, setelah hampir tiga tahun keterlibatan berkelanjutan, masyarakat mulai mengambil inisiatif lebih besar.

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Teluk Pambang menyelenggarakan kampanye kesadaran lingkungan, mulai bereksperimen dengan model ekonomi berbasis sumber daya mangrove, serta mengambil alih patroli, pemantauan, dan tugas koordinasi yang sebelumnya dipimpin oleh pihak luar. Apa yang dimulai sebagai program, kini berkembang menjadi gerakan yang dipimpin oleh masyarakat lokal.
Evolusi dari pendekatan berbasis komunitas menuju kepemilikan oleh komunitas harus menjadi standar baru jika Indonesia ingin mencapai target ambisiusnya dalam memulihkan lebih dari 600.000 hektare secara nasional. Tidak cukup hanya menghitung bibit yang ditanam atau luas lahan yang direstorasi. Keberhasilan sejati ditentukan olehseberapa dalam keterlibatan komunitas, seberapa besar kewenangan yang mereka miliki, dan seberapa efektif mereka dapat mempertahankan konservasi tanpa dukungan eksternal yang terus menerus.
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, meski memiliki keterbatasan, namun memberikan landasan hukum penting untuk menempatkan komunitas sebagai pusat tata kelola mangrove. Regulasi ini juga menekankan bahwa mangrove harus diperlakukan sebagai ekosistem yang terhubung dan berkesinambungan, bukan terfragmentasi oleh batas administratif.
Di seluruh lanskap mangrove Indonesia yang luas, kondisi untuk mewujudkan kepemilikan komunitas sebenarnya sudah ada. Sistem pengetahuan tradisional, peraturan lokal, dan klaim atas tanah adat menjadi fondasi yang kuat.
Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan kebijakan lokal yang lebih kuat, hak tenurial yang aman, mekanisme pembiayaan yang dirancang untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat lokal, serta motivasi untuk mereplikasi kesuksesan Teluk Pambang di tempat lain. Hal ini menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya perhatian global terhadap karbon biru, pasar karbon, pembiayaan iklim, dan solusi iklim berbasis laut.

Sebagai bagian dari komitmen iklim globalnya, dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang kedua, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara tanpa syarat dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Menyusul Hari Mangrove Internasional 2025 pada 26 Juli, mari kita ingat sebagai salah satu ekosistem karbon biru yang paling efektif, mangrove sangat penting untuk mencapai target-target ini. Namun, untuk memastikan bahwa upaya restorasi dan perlindungan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, kepemilikan komunitas dan prinsip keberlanjutan harus ditanamkan sejak awal.
Keduanya harus menjadi pilar utama dari setiap strategi karbon biru yang kredibel. Artinya, melibatkan aktor lokal dalam pengambilan keputusan, merancang kerangka pembagian manfaat dengan masukan komunitas, dan menyelaraskan ambisi global dengan realitas lokal yang nyata.